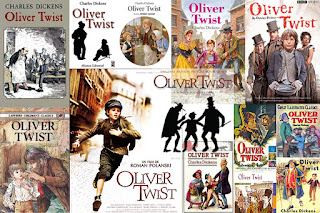Kongkalikong dan akrobat politik diperkirakan bakal memuncak pada tahun 2013 karena merupakan tahun yang menentukan bagi para elite politik untuk bermain dalam menyongsong Pemilu 2014. Akibatnya, kehidupan ekonomi akan tergencet.
Demikian benang merah dari diskusi Panel Ahli Media Group yang bertajuk Ekonomi Politik 2013 Menyongsong Pemilu 2014 di Kantor Media Indonesia, Kedoya, Jakarta Barat (4/12/2012). Hadir sebagai pembicara, pakar politik Yudi Latief, pakar hukum tata negara Andi Irmanputra Sidin, dan pengamat ekonomi Achmad Erani Yustika.
Tahun 2012 akan segera berakhir. Tahun baru otomatis bakal datang, dan sesudah nya, yakni tahun 2014, bangsa ini bakal direpotkan dengan hajatan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pemilihan presiden. Sudahkah bangsa ini sukses mengukir prestasi di bidang ekonomi dan politik?
Beberapa kali bangsa ini menggelar pemilu yang disebut-sebut paling demokratis setelah pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan rezim Orde Baru tumbang. Pemilu demokratis di era reformasi itu digadang-gadang mampu membawa perubahan, paling tidak di sektor ekonomi dan politik.
Pertanyaannya ialah dalam kurun waktu 14 tahun sejak reformasi bergulir, sudah mantapkah posisi ekonomi dan politik bangsa ini? Jawabnya, masih jauh dari apa yang diharapkan.
Padahal kalau mau ditelaah, 2013 sesungguhnya merupakan momentum ‘indah’ bagi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menetapkan sebagai ‘kisah kesuksesan’ pemerintahannya sejak ia memegang tongkat komando negeri ini sebagai presiden selama dua periode lewat pemilihan langsung.
Yudi Latief, Achmad Erani Yustika, Andi Irmanputra Sidin
Buang HandukNamun, momentum untuk menjadikan bangsa ini bangkit, baik di sektor ekonomi maupun politik, tidak dimanfaatkan dengan baik. Negara lagi-lagi dinilai belum mampu mengelola dan menggarap berbagai sumber daya alam yang dimiliki negeri ini. Indonesia kaya dengan sumber daya alam (pertambangan untuk energi). Tapi, bangsa ini selalu kedodoran mengelola produksi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah belum lama ini memperkirakan cadangan minyak nasional akan habis dalam 20 tahun mendatang, yakni pada tahun 2032, bila kebijakan pengetatan BBM bersubsidi tidak diterapkan. Alasan pemerintah, hal itu dimungkinkan sebab konsumsi BBM bersubsidi rata-rata meningkat 10% per tahun bila tidak ada penerapan pengetatan penggunaan BBM bersubsidi. Peningkatan volume BBM bersubsidi, masih menurut versi pemerintah, berisiko pada cadangan minyak yang akan cepat habis.
Jika memang faktanya demikian, bukankah itu merupakan sinyal bahwa sesungguhnya pemerintahan sekarang sudah berancang-ancang membuang handuk (tanda menyerah) karena tidak mampu mengelola negara?
BBM adalah kekayaan rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33, menikmati BBM (termasuk yang disubsidi) adalah sebagai wujud dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Ayat (1) pasal itu menyebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” sedangkan ayat (2) berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
Jelas bahwa BBM dan pengelolaannya, pertama-tama, harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, ketersediaannya juga harus jelas. BBM itu kebutuhan rakyat, harganya juga harus terjangkau oleh siapa pun. Distribusi dan harganya tidak boleh dibeda-bedakan, seperti premium hanya untuk rakyat tidak mampu, sedangkan orang kaya harus membeli jenis BBM yang harganya mahal. Dalam sebuah negara, tidak boleh ada diskriminasi.
Karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk menyatakan jika distribusi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, cadangan BBM akan habis. Soal beginian memang tidak masuk ranah pelanggaran hukum, tetapi merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi. Sekali lagi, jika memang faktanya seperti itu (cadangan BBM bersubsidi habis), itu pertanda pemerintah tengah bersiap-siap buang handuk pada 2013 mendatang.
Mengelola BBM, sehingga bisa dinikmati oleh siapa pun, merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, sungguh aneh jika negara kemudian ‘menuduh’ orang kaya yang membeli BBM bersubsidi sebagai ‘penjahat’. Membeli BBM bersubsidi adalah hak yang dijamin konstitusi. Bukankah kalangan the haves itu juga rakyat, dan memiliki hak yang sama untuk memilih dan membeli BBM yang diminati. Ini juga menjadi sinyal bahwa negara tidak mampu menjalankan amanat konstitusi.
Apa pun situasinya, 2013 yang sebentar lagi kita masuki ialah momentum lanjutan dari apa yang telah kita putuskan 14 tahun yang lalu (era reformasi). Sebelum 1998, negara dikritik karena menganut sistem otoriter. Pemerintahan Orde Baru ketika itu membunuh bibit-bibit ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Semuanya tersumbat.
Moral HazardKita saksikan ada moral hazard di sana. Kesuksesan ekonomi hanya mampir pada individu atau kelompok -kelompok tertentu. Rezim otoriter menutup akses siapa pun. Maka, ketika rezim tersebut tumbang, demokrasi menjadi pilihan, karena semuanya muak terhadap sistem yang diberlakukan.
Kekuatan ekonomi pada masa itu hanya berpusat di Jakarta. Ketimpangan ekonomi begitu sangat mencolok di daerah. Pembangunan ekonomi sangat proteksionis kepada kelompok-kelompok tertentu dan sangat masif. Mereka atau kekuatan-kekuatan ekonomi yang sudah telanjur eksis tak boleh diganggu.
Semua itu menjadikan ekonomi Indonesia tidak efisien. Para pelaku ekonomi dimanja oleh penguasa. Maka itu, jangan heran jika waktu itu pernah muncul istilah ekonomi pornografi sebab rezim ekonomi Orde Baru sudah berusia 30 tahun, tapi masih tetap disusui.
Setelah rezim Orde Baru selesai, kita merindukan semuanya berubah melalui jalan demokrasi. Dan agar perekonomian di daerah bergairah, otonomi daerah dijadikan opsi. Reformasi diharapkan bisa mengubah semuanya.
Hasilnya? Terjadi liberalisasi ekonomi. Celakanya lagi, pemerintah tidak menyusun regulasi yang mampu menggerakkan roda perekonomian yang ujung-ujungnya menyejahterakan rakyat. Di sektor ketenagakerjaan, misalnya, sebagian besar masih diisi oleh SDM yang cuma lulusan SMP/SMA.
Perusahaan asing masih mendominasi atau menguasai (75%) dunia usaha di Indonesia. Ketidakadilan pendapatan tetap ada di mana-mana. Ada 40 orang kaya di Indonesia yang kekayaannya senilai dengan 60% APBN. Roda perekonomian masih terkonsentrasi (45%) dan berputar di Pulau Jawa dan Sumatra.
Bandingkan pada masa sebelum orde reformasi bergulir, ketika 350 orang kaya di Indonesia menguasai perekonomian yang setara dengan 70% APBN. Artinya, terjadi jurang pemisah yang luar biasa dalam. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Di sisi lain, ikut dalam arus globalisasi ekonomi adalah sebuah pilihan yang tidak bisa dihindari. Dan negeri ini untuk sementara hanya bisa dimanfaatkan sebagai pasar bagi produk-produk negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 4%-6% memang baik, tapi ketahanan pangan masih jeblok dan rentan. Cadangan beras di Bulog hanya 4% dari kebutuhan nasional, sehingga sebagian besar beras yang kita konsumsi setiap hari adalah impor. Bandingkan dengan Thailand yang ‘Bulog’-nya di sana mampu menyiapkan stok pangan 20%, Brunei Darussalam (40%), dan Malaysia (30%).
Negara-negara tetangga itu tentu jauh lebih siap dibanding kita jika sewaktu-waktu ada turbulensi ekonomi yang melanda. Demokrasi yang dicanangkan saat reformasi diharapkan mampu mengubah perekonomian yang stagnan menjadi lebih dinamis. Akan tetapi, demokrasi yang disebut-sebut memberi kebebasan dan diharapkan mampu melahirkan kondisi yang lebih baik itu tetap tidak bisa menolong. Yang terjadi sekarang adalah demokrasi minus kesejahteraan. PDB memang naik, tapi sumbangan kenaikan PDB itu berasal dari orang asing.
Istana PasirKarena kehidupan ekonomi belum mampu mengubah kondisi bangsa, kerusakan moral ada di mana-mana. Korupsi adalah salah satunya. Sesungguhnya, kita sekarang ini berada di dalam istana pasir, karena kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dikuasai segelintir orang.
Ketidakadilan politik dan ekonomi masih terjadi di mana-mana. Ada yang mengatakan, jika rakyat makmur, keadilan akan datang dengan sendirinya. Pemikiran seperti ini jelas keliru. Sebab, orang miskin di negeri ini tidak mungkin harus menunggu makmur dulu baru bisa merasakan keadilan.
Demokrasi kelihatannya memang cantik, tapi kenyataannya malah mendatangkan hal-hal buruk. Kenyataan itulah yang sekarang sedang menimpa Indonesia dan akan berlanjut pada 2013. Penegakan demokrasi diharapkan mampu diikuti dengan penegakan hukum. Namun, faktanya, para penegak hukum yang diharapkan mampu menegakkan hukum itu justru malah menjadi public enemy yang demikian sempurna.
Untuk mencapai suatu demokrasi, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu harus sejalan dengan meritokrasi (berdasarkan keahlian) dan nomokrasi (penegakan hukum). Singkatnya, demokrasi butuh pemerintahan dengan otoritas yang kuat namun menjalankannya tidak dengan cara-cara yang otoriter.
Politik 2013Suasana dan iklim politik yang bakal terjadi pada tahun 2013 juga setali tiga uang dengan sektor ekonomi. Dunia politik masih dikuasai oleh kelompok elite yang bersinggasana di partai politik. Sistem politik yang ada saat ini tidak memungkinkan orang-orang cerdas di negeri ini menjadi presiden karena pencalonannya harus melalui partai politik yang sangat tertutup. Bahkan saking tertutupnya, orang-orang partai sendiri sulit mencalonkan diri menjadi presiden.
Pada 2013, dalam soal pencalonan presiden itu, diperkirakan kebiasaan atau tradisi ‘diam-diam mengumumkan nama calon presiden’ setelah orang-orang (elite) partai mengadakan rapat tertutup masih akan terjadi. Idealnya, pencalonan tokoh partai menjadi calon presiden adalah lewat konvensi seperti yang pernah dilakukan Partai Golkar.
Dengan konvensi, setiap kader partai punya peluang mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga sangat mungkin, jika konvensi ini digelar PDIP misalnya, nantinya nama yang muncul bukan Megawati Soekarnoputri. Begitu pula halnya dengan Partai Golkar, nama calon presiden yang muncul bisa saja bukan Aburizal Bakrie.
Terlepas dari cibiran banyak orang, kehadiran Rhoma Irama yang nekat mengklaim bahwa dirinya layak menjadi presiden untuk hajatan Pemilu 2014 patut kita apresiasi. Sebab, cara-cara seperti itulah yang sebenarnya kita harapkan jika kita memang berniat menghidupkan demokrasi.
Megawati, Aburizal Bakrie
Sebagai anak bangsa, tidak ada yang salah dalam niat ‘Raja Dangdut’ itu untuk menggantikan SBY. Persyaratan untuk menjadi presiden juga terpenuhi. Simak saja Pasal 6 UUD 1945/ Perubahan III ayat 1 yang menyebutkan, “Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden”.
Barangkali ganjalan bagi Bang Haji akan datang dari Pasal 6A (2), “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Namun, perkembangan terakhir, Partai Kebangkitan Bangsa memasukkan nama Rhoma sebagai kandidat capres. Bila memang akhirnya dua niat bertemu, langkah Rhoma menggantikan SBY bisa saja menjadi kenyataan.
Faktanya, kita memang mengalami kesulitan mencari ‘kesatria piningit’ lewat jalur formal. Maka itu jangan salahkan siapa-siapa jika yang muncul akhirnya adalah ‘kesatria bergitar’.
Sumber:Diskusi Media Group “Ekonomi Politik 2013 Menyongsong Pemilu 2014”MEDIA INDONESIA, 10 Desember 2012