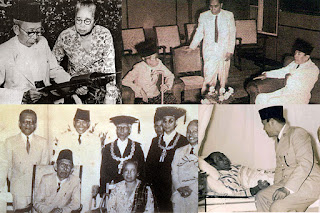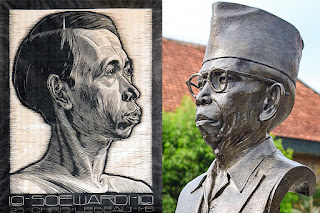Rabu, 24 April 2013, Cak Nun diundang sebagai pembicara dalam Program Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXXI, Tahun 2013 yang mengangkat tema: “Menyiapkan Kepemimpinan yang Tangguh dan Inovatif dalam Menghadapi Berbagai Perubahan dan Turbulensi yang Dihadapi Saat Ini”. Secara khusus, Cak Nun diminta untuk membawakan topik
Cultural Leadership. Program SESPIBI ini merupakan jenjang pendidikan karier tertinggi bagi pejabat Bank Indonesia (BI). Pesertanya berasal dari kepala-kepala divisi yang akan diangkat ke level direktur. Tahun ini ada 48 peserta, mayoritas berasal dari BI, sebagian yang lain berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ada satu orang yang berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Berangkat dari tawaran Cak Nun sebelum acara, sesi yang berlangsung dari pukul 08.30 sampai 11.30 itu dibagi menjadi dua. Satu jam pertama Cak Nun dimohon untuk berlaku sebagai “Kiai Ceret” untuk menuangkan pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan beliau terkait dengan tema yang dimaksud. Dua jam setelah itu barulah Cak Nun berlaku sebagai “Kiai Genthong” di mana para peserta bertindak sebagai subyek utama dalam diskusi,
nyidhuk (mengambil) apapun yang mereka ingin ketahui dan pelajari dari beliau.
“Saya pribadi mengenal Cak Nun sebagai pimpinan dari grup musik yang sangat saya suka, yakni Kiai Kanjeng. BI pernah mengundang Kiai Kanjeng untuk pentas di sini. Di samping itu, Cak Nun juga seorang sastrawan. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau baik berupa puisi maupun dalam bentuk-bentuk lain yang kebanyakan dalam bentuk sastra relijius,” ujar moderator acara memperkenalkan Cak Nun kepada para peserta.
“Banyak sekali pengalaman Cak Nun yang bisa ditimba, karena telah terbiasa bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Pengalaman Cak Nun terkait pula dengan kepemimpinan beliau dalam membawa misi-misi budaya, termasuk membentuk grup musik, dan juga membina anak sulungnya (Sabrang Mowo Damar Panuluh alias Noe) untuk menjadi vokalis handal di grup band Letto. Silahkan nanti kita tanya apa saja di sesi kedua.”
“Moderator kita ini terlalu terbiasa dengan kata benda, padahal yang nomor satu dalam hidup ini adalah kata kerja. Meskipun kata kerja itu pada tahap-tahap yang berbeda akan sampai juga pada kata benda, tapi sifatnya kehidupan adalah kata kerja,” ujar Cak Nun mengawali sesi pertama.
Kalau Anda melihat Indonesia sebagai kata benda, Anda akan kebingungan dengan Indonesia Orde Lama, Indonesia Orde Baru, Indonesia Reformasi. Tapi kalau Anda
ngomongnya Indonesia itu kata kerja, cara berpikir kita akan menjadi lebih dinamis dan relatif. Semua yang diceritakan tentang Emha tadi itu adalah kata benda-kata benda yang merupakan samaran-samaran hidup saya. Jadi aslinya saya tidak seperti itu.
“Yang kedua, saya tidak merasa punya kredibilitas di bidang apapun untuk berada di acara ini bersama Anda semua, tapi saya datang karena etika, karena sopan-santun, karena sudah diundang. Karena saya dianggap bisa
ngomong, ya sudah saya
ngomong. Bahwa nanti terbukti kalau saya tidak bisa memenuhi apa yang Anda minta, itu salahnya yang ngundang,” kata Cak Nun yang langsung disambut tawa para peserta.
“Nomor tiga, saya sengaja tidak pakai
assalamu ‘alaikum karena saya sudah
pakewuh sejak lama sekali sama Tuhan karena selama ini orang-orang Indonesia mengucapkan
assalamu ‘alaikum tapi tidak ada satu pun yang mengerti itu apa. Banyak sekali ucapan
assalamu ‘alaikum di sini, tapi mereka tidak bersungguh-sungguh ber-
assalamu ‘alaikum di antara mereka. Saya lihat Tuhan akhir-akhir ini banyak cemberut karena ini,” selorohnya.
Anda agaknya agak takut kalau sudah mulai ngomong tentang Tuhan. Maksud saya
gini lho,
assalamu ‘alaikum itu kan satu MOU (
Memorandum of Understanding) yang diucapkan oleh satu pihak ke pihak lain, dan lantas pihak lain menjawabnya. MOU ini ada beberapa tahap. Maka ketika saya mengucapkan assalamu ‘alaikum kepada Anda, berarti saya menyampaikan jaminan keselamatan Anda paling tidak dalam tiga hal.
Yang pertama, hartamu pasti selamat kalau sama saya. Saya tidak akan bikin
policy apapun yang akan merugikan hartamu. Yang kedua, martabatmu selamat di hadapan saya. Dan yang ketiga, keselamatan juga untuk nyawamu. Lalu kemudian Anda menjawab dengan
wa ‘alaikum salam, itu berarti Anda sudah sign MOU di antara kita untuk saling menjaga tiga hal itu.
Mohon maaf ini jadi kayak ceramah ustadz. Aslinya ustadz itu tidak ada di Quran, tidak ada di Hadits. Ustadz itu karangan kapitalisme. Itu caranya orang untuk cari duit. Sama seperti bank syariah. Seharusnya kalau sudah menjadi bank syariah kan dia bukan lagi bank umum, tapi nyatanya kan keduanya tetap ada. Misalkan bank Mandiri, walaupun sudah ada yang syariah (Mandiri Syariah), namun yang umum (konvensional) masih tetap ada. Jadi ternyata masalahnya (syariah atau tidak) bukan prinsip, tapi soal mana yang menguntungkan. Maka kalau untuk segmen tertentu pakai syariah, dan untuk segmen yang lain pakai yang biasa.
Cak Nun kemudian menjelaskan tahapan-tahapan dari penjaminan keselamatan yang terkandung dalam ucapan salam. Setelah ‘kontrak’
assalamu ‘alaikum, ada frasa
wa rahmatullah, kemudian ada
wa barakatuh.
Tuhan itu sudah kasih rahmat kepada Anda semua. Dia kasih hidung Anda mancung, kasih rambut Anda tumbuh, kasih Anda tidak perlu mengatur jam berapa Anda kencing, kasih batasan terhadap tinggi badan, kasih batasan pada pertumbuhan gigi. Kalau satu saja dicabut oleh-Nya, Anda sudah sangat kerepotan.
Kalau nggak karena Tuhan memberi batas-batas, celakalah hidup manusia. Itulah rahmat. Rahmat bukan hanya berupa limpahan rizqi, tapi juga dalam bentuk batasan-batasan rizqi. Ada orang yang celaka karena ingin melewati batasan itu. Maka Puji Tuhan yang telah membatasi.
Rahmat Tuhan ini harus kita
manage, harus kita kelola dengan aturan-aturan, dengan sistem-sistem hukum, dengan konstitusi sampai aturan-aturan pemerintah, keputusan presiden, kode etik di berbagai institusi, atau apa saja yang merupakan satu sistem kenegaraan atau kebudayaan atau peradaban, supaya ada transformasi dari rahmat menjadi barokah.
Kalau tidak ada pengelolaan ilmu dan sistem, maka padi tidak akan pernah menjadi beras, beras tidak akan menjadi nasi, nasi hanya akan berhenti menjadi nasi tanpa pernah jadi nasi gurih, nasi uduk. Itu semua kan butuh ilmu dan sistem pengelolaan.
Di antara rahmat dan barokah itu maka diperlukan negara, diperlukan BI, diperlukan sistem
banking, diperlukan kesenian, departemen-departemen. Ini disebut
ijtihad kalau dalam istilah agama, yaitu daya pikir yang terus-menerus untuk menguak bagaimana padi menjadi beras, menjadi nasi, dan menjadi aplikasi yang bermacam-macam.
Itulah kenapa saya bangga menjadi orang Indonesia, karena orang Indonesia merupakan satu-satunya negara, bangsa, etnik, yang punya kosakata detil mengenai beras. Kalau Bahasa Inggris hanya mengenal beras dalam kata
rice, kita menyebutnya sebagai padi atau pari ketika masih di sawah, gabah ketika sudah dipanen, beras ketika sudah digiling, dan nasi atau
sego ketika sudah dimasak. Itu kan karena kebudayaan kita jauh lebih tua dan jauh lebih matang daripada kebudayaan mereka.
Kembali ke konsep rahmat dan barokah, menurut saya BI adalah pemimpin transformasi dari padi ke beras, dari beras ke nasi. Wah, kalau langsung ke BI agak tidak enak juga saya, karena kalau
ngomong BI kita bisa ke mana-mana, bisa ke Neolib, bisa ke IMF, Briggs. Saya nggak enak, dan saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa kok. Saya cinta sama bangsa Indonesia dan saya maklum kalau presiden bilang kekayaannya ada 9 M. Nggak apa-apa, karena kebohongan
kan tidak bisa dihindarkan di Indonesia ini.
Bebek Slamet juga bakal ketawa kalau dengar presiden kita kekayaannya cuma 9 M,
wong Bebek Slamet saja puluhan miliar. Cuma kan
nggak bisa
nggak bohong kalau di Indonesia. Indonesia bukan tanah yang subur untuk kejujuran. Gimana mau
nggak bohong, nanti orang lain yang bohongin kita. Gimana mau nggak curang, dia curang sama kita kok. Kenapa harus berbuat baik ke mereka, mereka saja nggak berbuat baik ke kita. Jadi di Indonesia ini saya sangat maklum kalau ada banyak orang korupsi, membunuh, karena mereka memang tidak aman di sini.
Mau berbuat baik nggak aman, agama dieksploitasi, dan budaya kemiskinan kita sangat tinggi. Orang-orang kaya itu sangat punya budaya dan mental kemiskinan. Budaya kemiskinan itu artinya orang yang sangat tergantung kepada keamanan materi. Kalau saya kan orang agak kaya, artinya saya
nggak jelas punya uang berapa, bisa makan atau tidak, anak saya sekolahnya
gimana, itu benar-benar urusan dinamis setiap hari. Bisa apa
nggak, saya
nggak tahu. Karena saya kaya raya,
wis matek urip bah-bah lah (mau hidup atau mau mati terserahlah).
Kebanyakan orang kan nggak punya keberanian untuk seperti itu, maka mereka harus terus memastikan laba sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya, maka mereka pakai ideologi kapitalisme dan seterusnya.
Kembali ke
assalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatuh saya kira halangan kita sekarang ini adalah kita terus bertengkar di antara rahmat dan barokah. Nggak ada sistem yang kita sepakati. Ganti-ganti terus dari Orla ke Orba, ganti lagi di Reformasi. Kita tahun 2014 akan mengalami perubahan-perubahan lagi. Para investor di seluruh dunia juga sudah siap-siap karena dianggap akan ada renasionalisasi aset-aset negara, seperti misalnya ada regulasi yang melarang ekspor bahan mentah. Akan ada perubahan-perubahan besar dan yang disangka akan melakukan perubahan itu adalah salah seorang mantu mantan presiden, padahal bukan dia. Akan ada orang lain yang melakukan hal-hal itu. Ini pokoknya dunia sedang berspekulasi. Kalau saya kembalikan ke BI, saya kira BI adalah pemimpin transformasi rahmat supaya jadi barokah, sebab banyak rahmat tidak menjadi barokah.
Bedanya rahmat dan barokah itu teori universalnya seperti ini: hujan itu rahmat karena dia tidak memilih pada siapa dia datang. Siapa saja yang keluar ruangan, dia kehujanan. Tuhan ini nggak milih, misal orang yang korupsi tidak dikenai hujan. Rahmat itu dikasih Tuhan ke siapa saja. Maling ya dikasih rahmat. Siapa saja (dikasih rahmat).
Uang curian untuk beli soto itu ya tetap enak sotonya, karena sifatnya sifat rahmat. Kalau barokah itu sesuatu yang telah diregulasi dengan kemauan-kemauan dan aturan-aturan Tuhan. Maka, orang kaya bisa bangkrut kalau urusannya barokah. Sementara orang yang tidak ‘kaya-kaya amat’ bisa lancar hidupnya.
Menurut saya BI adalah ujung tombak dari pengaturan lalu-lintas rizqi dari rahmat Allah itu supaya menjadi barokah bagi seluruh bangsa Indonesia.
Empat Jenis ManusiaKalau soal kepemimpinan budaya, saya kira tidak sukar. Kita bisa ambil dari sangat banyak wacana, cuma apa itu masalahnya di BI? Maka doa saya adalah; ini yang saya hadapi adalah manusia-manusia BI baru yang mengambil baiknya dari Orba, mengambil baiknya dari Reformasi, manusia-manusia BI baru yang tidak harus merupakan produk dari BI yang sebelum-sebelumnya, karena ada dinamika yang bermacam-macam. Pokoknya ini adalah generasi terbaru yang mengambil yang terbaik untuk bangsa, untuk rakyat, sehingga dia menjadi manusia BI baru sebagaimana sekarang lahir juga manusia-manusia Indonesia baru dari generasi muda yang bukan merupakan produk dari televisi yang kayak gitu, dari koran yang kayak gitu, dari kebudayaan yang kayak gitu, dari berbagai manipulasi agama yang terus-menerus.
Agama ini dikapitalisasi
nggak karu-karuan. Kata ‘syariat’ pun dikapitalisasi. Kata ‘Al’ jadi jualan laris, kata ‘Gus’ jadi barang dagangan, juga kata ‘wali’ yang menjadi marketable. Gus Dur itu sekarang jadi wali kesepuluh. Jadi langsung loncat dari Sunan Kalijaga ke Gus Dur, tanpa bapaknya dan mbahnya, Gus Dur jadi wali. Padahal peristiwa 10 November itu hasil dari resolusi jihad Bapak dan Mbahnya Gus Dur. NU besar juga karena yang mendirikan Mbahnya Gus Dur. Sekarang yang jadi wali malah Gus Dur.
Itu sudah menjadi komoditas. Yang kemarin nyetiri saya saja sekarang jadi Gus, jadi pejabat tinggi di provinsi. Kemarin dia masih ngambil ban bekas, sekarang sudah jadi Gus. Dan Gus ini nggak bisa dilacak asal-usulnya, dan orang modern tidak peduli apa itu Gus, apa itu kiai, apa itu syekh, habib, maulana. Ini sudah jadi komoditas semua.
Kalau saya misalnya mau jadi wali, gampang sekarang ini. Saya tinggal pergi ke travel biro atau ke televisi. Padahal kan;
laa ya’riful wali ilal wali. Sekarang jadi;
laa ya’riful wali ilal travel biro wa EO. EO itu yang menciptakan Gus Dur jadi wali. Sampai sekarang ini bahkan ada walisongo Jawa Timur. Kalau Walisongo kan ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekarang ada Walisongo Jawa Timur, yang dari Walisongo dikurangi 4, kemudian empatnya dicarikan di Jawa Timur. Caranya mencari adalah yang gampang dilewati rute bus travelnya. Mereka bikin wali-wali yang mudah dicapai oleh travel. Itu yang namanya budaya kemiskinan. Orang sudah tidak percaya kepada rizqi Allah. Orang hanya percaya pada apa yang dia ambil, pada apa yang dia curi, apa yang dia
mark-up, apa yang dia kolusi, apa yang dia manipulasi.
Kalau Sunan Kalijaga kan doanya
Allahuma tuhno, Allahuma tekno. Itu wiridannya.
Tuhno itu kalau butuh ono, kalau pas butuh ada.
Tekno itu kalau entek ono, kalau pas habis ada. Sunan Kalijaga membatasi umatnya di situ. Kamu nggak usah kaya tapi kalau pas butuh, ada. Saya penganut ini. Saya
nggak kaya, tapi asal pas saya butuh selalu ada,
mbuh bagaimana caranya. Butuh di sini bukan hanya uang, tapi juga apa saja. Saya tidak percaya ada kekayaan yang sungguhan, saya tidak percaya ada orang kuat yang sungguhan, saya tidak percaya ada orang sakti.
Kalau saya singkat, kebudayaan kita itu luar biasa kayanya. Kita bisa ambil kearifan kepemimpinan dari Jawa, Madura, Sunda, Mandar, Bugis, tinggal ambil yang mana. Kita bisa ambil sedikit dari budaya, sedikit dari agama.
Misalnya Pak Harto, dalam memimpin dia cuma pakai dua ilmu, yaitu
pranoto mongso dan
katuranggan.
Pranoto mongso adalah kemampuan untuk membaca musim. Ini dunia sedang begini, negara sedang begitu, cocoknya ikut Uni Soviet atau Amerika atau China, seperti itulah yang dinamakan membaca musim. Pak Harto tidak menggunakan ilmu-ilmu modern tapi dia merasakan dengan ilmu musim. Dari situ dia ambil
policy dasar. Untuk menerapkan
policy yang sudah ditentukan dengan
pranoto mongso tadi, Pak Harto butuh memilih orang. Menteri Penerangan siapa, Menko ini siapa, Direktur BI siapa. Dalam menentukan siapa diletakkan di posisi mana, Pak Harto pakai ilmu katuranggan.
Katuranggan itu berasal dari kata
turangga, artinya kuda. Jadi, ilmu tentang watak berasal-usul dari pengetahuan para pemelihara kuda terhadap . Kalau orang mempelajari kuda, dia akan melihat berbagai macam watak manusia terdapat pada kuda. Kalau Anda ahli kuda, cukup dengan melihat gambar di lutut depannya saja Anda sudah tahu umurnya berapa, larinya secepat apa, staminanya tinggi apa tidak. Ilmu kuda ini kemudian ditransfer menjadi ilmu tentang watak manusia,
katurangganing manungsa.
Jadi kalau mau pilih staf, kita mesti mengenal wataknya. Watak ini berdasarkan konfigurasi atau terminologi apa? Kalau dalam pandangan politik, ada empat jenis manusia di setiap lingkungan, yaitu manusia pencetus, manusia pendiri, manusia pemelihara, dan manusia pendobrak.
Manusia pencetus adalah manusia yang selalu membicarakan hal-hal baru, selalu gelisah, tapi kerjaannya cuma begitu. Dia digaji untuk itu saja, jangan disuruh tertib di kantor. Begitu sudah mencetuskan ide baru, habis staminanya. Dia adalah bagian mencetuskan. Jangan disuruh mendirikan atau memelihara, karena pasti hancur nanti. Sehebat-hebat pencetus, dia tidak punya keberanian sejarah untuk mendirikan. Dia ada di belakang
founding fathers.
Manusia pendiri atau perintis adalah manusia-manusia yang berani membangun. Merekalah yang bikin NKRI, bikin ini, bikin itu. Mereka adalah jenis manusia yang mendapat
fadhilah dari Tuhan untuk mendirikan. Tapi pendiri juga belum tentu mampu memelihara, maka mayoritas manusia sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi manusia pemelihara.
Manusia pemelihara nggak ikut berpikir, nggak ikut mencari, nggak ikut mendirikan, tapi begitu sudah ada, dia yang setia memelihara. Pegawai negeri yang di bawah-bawah itu kan biasanya
katuranggan pemelihara. Dia rajin, absen pagi dan sore, wataknya pemelihara.
Jenis keempat adalah manusia pendobrak. Karakternya hampir mirip dengan manusia jenis pertama, yakni pencetus. Pendobrak ini bagian yang nggak setuju terus. Semua dibantah olehnya. Dia bisanya mengkritisi, tapi giliran disuruh bikin nggak bisa. Dia ini bagian nyacat atau mencela. Ada manusia yang memang oleh Tuhan diijinkan untuk menjadi juru cela. Maka jangan kaget kalau di antara kita ada yang ahli di bagian situ. Selama ini kan yang ahli atau pakar itu kan yang ekspertasinya di wilayah kedua atau ketiga, padahal ekspertasi kan luas. Ada orang yang memang kerjaannya nyacat terus
ben dino, dan itu bagus untuk kita yang memang ingin dinamis. Orang ini kalau tidak dibayar akan berbahaya bagi masyarakat, jadi mending bayar dia khusus untuk mencela di wilayah tertentu. Di wilayah selain itu, jangan mencela siapa-siapa. Dia punya kecerdasan untuk mencela, tapi dia hanya diperbolehkan mencela di ruang rapat kantor saja
lho ya, di luar kantor tidak boleh. Di luar itu dia harus berbudaya.
Berbudaya itu mencari yang baik dari yang buruk-buruk. Kalau yang terjadi di masyarakat sekarang kan justru mencari yang buruk-buruk dari yang baik. Ada orang baik dicari buruknya terus, sementara pekerjaan kebudayaan adalah ada orang seburuk apapun, kita cari baiknya, hingga kita nanti sampai di tahap di mana tidak ada yang tidak indah, tidak ada yang tidak nikmat, tidak ada yang tidak berguna. Ibaratnya dalam musik, tidak ada yang fals.
Fals itu tidak ada. Yang ada adalah bunyi tidak terletak di tempatnya bersama harmoninya. Kalau dia diletakkan berjejer dengan yang satu konfigurasi dengan dia, dia nggak fals. Ini kalau seandainya
workshop musik, saya tunjukkan kepada Anda. Dia punya konfigurasi harmoni sendiri.
Tidak ada yang buruk, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian dalam hidup ini. Kita pernah mengalami kehancuran saat Orba, Orla, Reformasi, banyak sekali, tapi saya melihat tidak ada masalah. Memang hidup seperti itu. Yang penting kita tahu yang disebut manajemen itu apa. Manajeman itu bukan bagaimana menyusun uang. Kalau saya, manajemen adalah bagaimana tidak punya kerjaan tapi bisa nyekolahke anak-anak. Itu kan manajemen banget. Bagaimana nggak punya gaji tetap tapi
bisa survive, itulah manajemen.
Nek gajimu sakmene digawe ngene, dudu manajemen iku, tapi kasir.Manajemen itu bagaimana kita tidak punya beras tapi bisa bikin nasi. Kalau dalam al-Quran namanya
min haitsu laa yahtasib. Allah memberimu rizqi melalui jalan dan metode yang di luar perhitunganmu. Dan itu adalah jaminan Allah setiap hari kepada orang yang selalu meletakkan hatinya dekat dengan Dia.
Saya pribadi bisa mendapatkan
cash dari langit. Satu contoh, saya didatangi kiai-kiai tua, ada di antaranya yang sudah 94 tahun usianya. Saya nangis karena nggak punya uang untuk
nyangoni, maka saya masuk kamar, wudlu, kemudian sisiran. Di atas lemari saya dapat 40 juta,
cash. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi, tapi syaratnya adalah saya tidak boleh mengambil sedikit pun untuk saya sendiri. Maka saya bagikan semua kepada tamu-tamu saya itu.
Tapi orang Indonesia kan nggak percaya sama Tuhan, maka kerjaannya mencuri terus, curang terus. Dia tidak percaya sama begitu banyak kemungkinan rizqi dalam kehidupan. Saya punya sekolahan, lebih banyak daripada yang didirikan oleh Direktur BI. Saya bisa mengadakan forum-forum Padhangmbulan setiap bulan di 6 kota, sekarang sudah 21 tahun, saya biayai sendiri. Dengan massa ratusan atau ribuan, forum-forum saya berlangsung tanpa sponsor, tanpa biaya dari siapa-siapa. Tanpa keamanan, tanpa izin, dan itu sudah semenjak Orba. Orang datang dari jam delapan malam sampai jam tiga pagi, sampai hari ini. Kemarin di TIM kami sampai jam 03.30, di Jogja tanggal 17 sampai jam 04.00, berlangsung terus-menerus karena
min haitsu laa yahtasib.Allah itu bukan milik para ustadz. Allah adalah milik kita semua, Dia sangat dekat sama kita. Dia sangat lucu, penuh humor, sangat penuh kasih-sayang. Dia tidak membutuhkan sopan-santun yang pura-pura.
Tentang ilmu
katuranggan jelas ya. Itulah kenapa Pak Harto memilih Harmoko untuk menjadi Menteri Penerangan sampai akhir meskipun kita nggak suka. Pak Harto tahu persis bahwa Pak Harmoko adalah tipe pemelihara. Sampai hari ini dia masih memelihara apa yang bisa dia pelihara. Ini saya tanya langsung ke Pak Harto mengapa dia pindah dari Pak Moerdani, padahal Pak Moerdani itu berjasa sama Pak Harto, dia menemukan dukunnya Pak Harto yang ke-39 di Aceh sehingga Benny Moerdani diangkat menjadi Dukun Gajah Putih. Sebelum itu teorinya ada 39 dukun Pak Harto, tapi baru ketemu 38. Saya ketemu dukun-dukunnya Pak Harto di mana-mana.
Tentang dukun ini juga ada teorinya sendiri. Dukun itu apa, kiai itu apa. Anda jangan salah sangka bahwa dukun ini pasti jelek dan kiai pasti baik, karena dukun masih bekerja untuk mendapat uang, sementara kiai biasanya nggak kerja tapi dapat uang. Jadi kan masih mending dukun.
Belajar Kepemimpinan dari Lokalitas yang ArifUntuk kepemimpinan, kita bisa belajar kepada Ki Hajar Dewantara. Pemimpin itu nomor satu harus ing ngarso sung tulodho, mampu memberi teladan. Teladannya bukan hanya dalam hal akhlak tapi juga dalam keterampilan, dalam profesionalisme, dalam kepekaan, dalam kedekatan budaya dengan karyawan. Teladan yang saya maksud adalah keteladanan yang utuh.
Kalau dia sudah bisa mempengaruhi karyawan atau bawahannya untuk beratmosfer seperti dia, maka kemudian dia tidak perlu menjadi contoh lagi. Tahap kedua adalah
ing madya mangun karso, bercampur di antara semua anak buahnya untuk melakukan apa-apa yang telah dia teladankan sebelumnya.
Kemudian tahap ketiga adalah tut wuri handayani. Syarat kepemimpinan kebudayaan, semua pemimpin itu menyiapkan dirinya untuk tut wuri handayani, bukan dari presiden malah jadi ketua Demokrat. Itu kan hanya mungkin dilakukan oleh orang pikun. Dia harusnya makin lama makin mandhita, makin siap untuk tidak menjadi apa-apa. Dia harusnya bersih dan tetap dihormati setelah tidak menjadi presiden, maka dia
tut wuri handayani. Kalau sekarang kan dia malah
ing ngarso ora tulodho.Konsep dari Ki Hajar Dewantara ini sangat jelas
kok. Sekarang Taman Siswa ‘mati’ karena ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara tidak kita akselerasi. Kita lebih percaya pada Cornell atau Berkeley, kita lebih percaya pada filosofi Barat.
Padahal Ki Hajar atau Ki Ajar ini kalau di Jawa merupakan sebutan bagi orang yang dianggap mempunyai ilmu yang melebihi ilmu masyarakat umum. Kalau ilmu yang dimiliki adalah ilmu agama, maka dia disebut
Yai. Tapi setiap orang Jawa dalam sopan-santun kebahasaan menambah nama orang dengan
Ki. Yai ditambah dengan
Ki, menjadi Kiyai.
Tapi diam-diam kita telah ‘menghancurkan’ Ki Hajar Dewantara dengan menghancurkan filosofi dan kosakata kita. Sekarang kata ‘ajar’ atau ‘hajar’ diplesetkan secara negatif dengan arti ‘memukuli’. Ya sudah, hancur kan jadinya?
Contoh lain adalah kata ‘akal’. Dalam Bahasa Arab, kata kerja dari
‘aql adalah ya’qil. Ya’qil merupakan pekerjaan nomor satu bagi manusia. Allah selalu mengatakan
afala ta’qiluun, kenapa kamu tidak pakai akal. Mengakali seharusnya berarti memperlakukan segala sesuatu dengan akal. Tapi sekarang ‘mengakali’ artinya mencurangi, meliciki. Ini kan pengkhianatan sangat besar terhadap bahasa-Nya Tuhan. Berapa ratus kali dalam al-Quran kata itu disebut?
Kata ‘ajar’ ini khas Jawa. Nabi Ismail lahir dari seorang ibu bernama Hajar. Hajar ini orang luar Arab yang nggak ngerti geografi Arab, nggak ngerti di mana sumber air, maka dia bolak-balik mencari air sampai akhirnya ketemu air zam-zam itu. Hajar ini kan bukan orang Arab. Kita cari ke mana-mana, ke Rusia, ke Afrika, dan cuma di Jawa kita temukan kata ‘hajar’ yang paling relevan. Berarti istrinya Ibrahim yang baru ini sepertinya orang Jawa –atau katakanlah orang Indonesia.
Hajar punya anak Ismail yang kemudian menurunkan orang Arab. Kalau dari istri yang satunya, lahir Ishaq. Turunan Ishaq menjadi Yahudi. Dunia ini dikuasai oleh dua klan itu. Yang punya duit adalah turunan Ismail, (namun) yang mengelola duit adalah turunan Ishaq, seperti Soros, IMF.
Nah, kita ini masalahnya ada di perempatan jalan. Kita ini turunan yang mana? Ataukah jangan-jangan kita lebih tua daripada Ibrahim?
Maka suatu hari jangan mau taat sama (klan) Ismail dan Ishaq, karena mereka adalah cucu-cucu kita. BI pada suatu hari harus menjadi lembaga keuangan dunia, dan Indonesia yang mengatur keuangan dunia karena kekayaan Allah di muka bumi dipusatkan di Indonesia. Jangan boleh Freeport seenaknya.
Bersambung ….