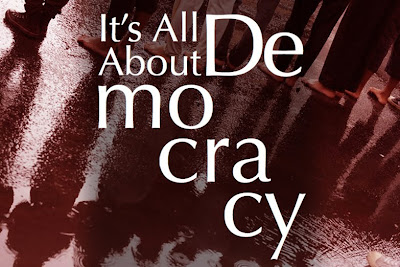Susno Duadji bergegas meninggalkan rumahnya di Puri Cinere, Depok, Selasa sore pekan lalu. Padahal baru dua jam sebelumnya, jenderal polisi berbintang tiga itu masuk rumah, untuk diwawancarai Tempo. "Ada pesan pendek dari anak buah saya di Mabes Polri: saya harus waspada satu," katanya. Setiap malam, tidurnya berpindah-pindah. "Saya takut di-Munir-kan," kata Susno, berbisik. Matanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Munir adalah aktivis hak asasi manusia yang tewas diracun pada 2004.
Tak hanya itu. Oleh istrinya, Susno kini dilarang minum kopi. Sebelum wawancara dimulai, dia sempat berbisik kepada pelayannya, minta dibuatkan segelas minuman barkafein itu. "Supaya tidak ngantuk," katanya. Tapi yang datang malah segelas besar teh hangat. "Kata Ibu tidak boleh," ujar si pembantu. Susno merengut, tapi kemudian mengakui, "Kesehatan saya memang agak drop," tuturnya.
Wajar kalau Susno susah tidur dan gelisah. Tudingannya tentang sepak terjang para makelar kasus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri membuatnya berhadap-hadapan dengan banyak mantan koleganya. Pekan lalu, dua kali dia diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), sebelum akhirnya ditetapkan sebagai terperiksa. "Itu sama saja jadi tersangka," katanya, mendengus. "Buktikan dulu omongan saya tentang kasus ini," kata Susno. "Kalau tidak terbukti, saya akan sukarela masuk bui." Ketika dipanggil untuk ketiga kalinya akhir pekan lalu, Susno menolak hadir.
Tindak-tanduk Susno yang menantang membuat panas banyak jenderal. Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sempat berkeras tak mau menindaklanjuti laporan Susno soal dugaan makelar kasus dalam kasus pencucian uang oleh pegawai Direktorat Pajak, Gayus Tambunan. Bambang baru melunak setelah Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemuinya, Kamis pekan lalu. "Memang ada kejanggalan dalam penyidikan, ada sesuatu," katanya. Sebuah tim independen lalu dibentuk untuk menelusuri dugaan kongkalikong itu.
Aroma perseteruan antarperwira berbintang di markas polisi tercium keras. Banyak yang menduga pemberhentian Susno yang mendadak sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) pada November 2009 adalah pangkalnya.
"Saya tidak kecewa dicopot," kata pria kelahiran Pagar Alam, Palembang, 56 tahun lalu ini. Dia memang sempat menyepi ke kampung halaman, sehari setelah dia menerima telegram rahasia pemberhentiannya. Setelah lima hari di Palembang, Susno kembali ke Jakarta pada 30 November untuk upacara serah-terima jabatan. "Saya rela," katanya.
Mantan Kepala Polda (Kapolda) Jawa Barat ini mengaku baru terusik ketika Mabes Polri mempersoalkan kehadirannya di persidangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Januari lalu. Ketika bersaksi di sana, Susno mengaku tidak tahu-menahu soal penyidikan Antasari. Dia menjelaskan kasus Antasari dikendalikan langsung oleh Kepala Polri.
Dua pekan kemudian, Susno muncul lagi. Kali ini di Senayan, menjadi saksi untuk Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah menelisik kasus pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Di sana Susno lagi-lagi bikin berita. Dia meninggalkan dokumen yang menyatakan upaya polisi menyelidiki kasus Century tertunda karena salah satu pejabat yang bakal diperiksa adalah calon wakil presiden Boediono.
Melihat gelagat Susno mulai "liar", Mabes Polri pun bereaksi. Dia dipanggil Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk pertama kalinya, tiga bulan lalu. "Saat itulah saya mulai marah," kata Susno terus terang. Wajahnya mengeras. Berkali-kali dia menyebut "saya ini mantan Kabareskrim" atau "saya ini jenderal bintang tiga" dengan nada geram.
Mabes Polri bukannya tidak berbuat apa pun untuk meredam Susno. Tatkala insiden kesaksian di sidang Antasari mencuat, Kepala Badan Intelijen Irjen Saleh Saaf sempat mendatangi kediaman Susno. Campur tangan Saleh ketika itu bahkan sampai membatalkan upaya Divisi Propam memeriksa Susno. Kepala Divisi Humas Irjen Edward Aritonang juga sempat dua kali menemui Susno. "Tidak saya saja. Ada beberapa kawan yang satu angkatan dengan Pak Susno," kata Edward pekan lalu.
Pertemuan berlangsung dua pekan lalu di sebuah hotel di kawasan Mahakam, tak jauh dari Mabes Polri. Di sana para jenderal dan komisaris besar dari angkatan 1977 ini membujuk Susno agar tak bikin ramai di luar institusi. "Kami sama-sama setuju mereformasi polisi, tapi panggungnya di dalam saja," kata Edward. Susno saat itu tak banyak bicara. "Dia hanya bilang akan mempertimbangkan masukan kami," kata Edward.
Tapi tampaknya Susno tak peduli. Kepada Tempo, dengan tersirat dia mengaku perlawanannya dirancang matang. "Saya sudah menghitung semua risikonya," katanya. Selain menerbitkan buku, Susno mempersiapkan "senjata" lain: dokumen.
Sejumlah sumber Tempo di kepolisian mengatakan Susno pernah minta dibelikan tiga brankas besar, sesaat sebelum dicopot dari kursi Kepala Badan Reserse. Susno tak menyangkal cerita itu. "Saya pakai untuk menyimpan berkas tentang sejumlah kasus lain di kepolisian," katanya. Kasus apa? Susno bungkam. Dia hanya sesumbar, "peluru" itu baru akan dipakai jika dia terpojok. "Atau kalau terjadi apa-apa pada saya," kata Susno serius.
Seteru Susno di Mabes Polri tak percaya pada ancaman itu. "Saya kok tidak yakin ada brankas isinya dokumen. Boleh tidak kita lihat sama-sama?" kata Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Raja Erizman dengan sinis. Pekan lalu bahkan beredar berkas "dosa-dosa Susno" di Trujonoyo, markas besar polisi. Isinya macam-macam dugaan "permainan" Susno ketika masih berjaya. Misalnya soal kepemilikan rumahnya yang sampai 16 buah, kasus-kasus korupsi yang disetop penyidikannya selama dia menjabat Kabareskrim, sampai tudingan dia "memelihara" makelar kasus sendiri. "Ada transfer uang dari si makelar langsung ke rekening Susno," kata sumber Tempo.
Keterlibatan Susno dalam kriminalisasi dua pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi akhir tahun lalu juga diungkit. Kedekatannya dengan Anggodo Widjojo, yang kini tersangka kasus penyuapan di KPK, misalnya, dibuka lagi. Dia bahkan dituduh merekayasa teror kepada dirinya sendiri.
Dimintai konfirmasi, Susno sudah punya jawaban. "Saya punya banyak rumah, karena saya jual-beli properti," katanya. Dia mengaku mengembangkan bisnis macam-macam sejak "sebelum jadi polisi". Soal makelar kasus, dia pasang badan. "Nama-nama yang disebut itu kawan saya sejak letkol, tapi mereka tidak pernah bawa kasus. Silakan diperiksa," katanya. Soal rekayasa pesan pendek berisi ancaman? "Kalau mereka yakin saya bersalah, ayo tangkap saja."
Gebrakan Susno menantang pimpinan Polri membuat sebagian orang curiga pada motifnya. Buku “Mereka Menuduh Saya”, yang dipromosikan Susno ke mana-mana, misalnya, jelas-jelas berisi harapan agar mantan Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu direhabilitasi dan diangkat menjadi Kapolri atau bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Bak gayung bersambut, sejumlah anggota DPR mulai berkoar mengirim sinyal serupa.
Kursi Ketua KPK saat ini memang kosong sepeninggal Tumpak Hatorangan Panggabean yang mengundurkan diri. Kalau tidak diperpanjang Presiden, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pun akan pensiun akhir 2010 ini. "Saya tahu diri. Masak orang yang tidak dipakai di polisi mau memimpin KPK?" Susno membantah. Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman menguatkan. "Pencalonan pimpinan KPK itu otoritas pemerintah, tidak bisa dicampuri parlemen."
Wahyu Dhyatmika, Sutarto
http://majalah.tempointeraktif.com//id/arsip/2010/03/29/LU/mbm.20100329.LU133143.id.html