
DEMOKRASI dewasa ini memang sulit, karena ia sekaligus merupakan filosofi, cara hidup, agama, dan lagi pula bentuk pemerintahan. Keaneka-ragaman signifikansi yang melekat pada watak demokrasi bukanlah berasal dari efektivitasnya, melainkan jauh lebih banyak dari ide yang dipegang orang tentang demokrasi itu pada saat makhluk ini mempercayakan kepadanya harapan akan kehidupan yang lebih baik. Memisahkan realitas dan harapan dalam demokrasi itu akan mengaburkan tidak hanya dinamisme yang menggerakkannya, tapi juga lembaga-lembaganya yang positif, karena makna lembaga-lembaga tersebut bergantung pada mistik yang dijelmakannya.
Demokrasi menjadi samar ketika terpaksa diterapkan secara tidak langsung. Penghayatannya yang baik dan benar memerlukan daya pikir abstrak yang kuat, baik di kalangan yang diperintah maupun yang memerintah. Bila kondisi ini tidak terpenuhi, pasti terjadi frustrasi, kekisruhan, kekecewaan, dan penipuan kerah putih, disengaja atau tidak. Pengertian demokrasi jauh lebih simpel daripada penerapan pengertian itu demi mentransformasikan ide menjadi realitas. Kita mudah membuat abstraksi literer, artistik, matematis, atau ilmiah, tapi tidak dalam abstraksi praksis.
Selaku pengertian, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat (A), oleh rakyat (B), dan untuk rakyat (C). Secara literer, ketiga kategori rakyat ini -A, B, C- merupakan sarana, tapi ia tidak serupa dalam praksis, bahkan bisa berlawanan. Ketidakserupaan itu merupakan sumber kekecewaan terhadap "demokrasi" itu sendiri dari semua orang dan lembaga yang berkepentingan dalam politik.
Bayangkan! Rakyat A adalah penduduk berstatus warga (citizen). Ia dipahami sebagai makhluk abstrak, suatu entitas global, tidak terbelah-belah, identik, tanpa kelas, betul-betul homogen, jadi diabstrakkan dari realitas sosiologis. Keanekaragaman riil dari para individu direduksi ke satu penyebut umum -common denominator- yaitu warga. Konsep idiil dan abstrak dari kewargaan ini langsung dikaitkan dengan konsep idiil dari kebangsaan. Rasionale dari keterkaitan ini adalah kedaulatan warga yang berasal dari hak-hak politik kerakyatannya. Ia menjadi semakin kukuh dan prinsipiil ketika negara, sejak revolusi Amerika dan Prancis, ditanggapi sebagai entitas substansial yang mewadahi bangsa dan berbentuk republik demokratis. Kelebihan demokrasi terhadap lain-lain formula pemerintahan adalah apa yang ia haramkan, yaitu kekuasaan otoritas yang tidak berasal dari rakyat A.
Walaupun berdaulat penuh, tidak semua warga bisa ikut langsung mengendalikan pemerintahan. Jadi, perlu ada pilihan. Sistem pemilihan ini menjadi keniscayaan, mengingat dewasa ini demokrasi menjadi tidak langsung. Artinya, rakyat yang berdaulat itu terpaksa mendelegasikan otoritas dan tanggung jawabnya atas pemerintahan kepada orang-orang tertentu di antara sesamanya. Maka warga A, makhluk abstrak ini, pada waktu tertentu diundang ke kotak suara untuk menyatakan pilihan dan/atau pendapatnya. Itulah sebabnya mengapa disebut "dari" rakyat.
Orang-orang yang terpilih inilah yang menduduki kursi di jajaran legislatif dengan label "wakil rakyat" dari kategori A. Di jajaran eksekutif, hanya petinggi-petinggi terpenting (presiden dan wakilnya, kepala daerah otonom dan wakilnya) yang dipilih langsung oleh rakyat atau oleh "wakil rakyat". Namun sebagian besar pada umumnya ditetapkan berdasarkan kemampuan teknis yang banyak-sedikitnya terkait dengan prestasi pendidikan formal dan pengalaman kerja. Demikian pula halnya dengan pejabat-pejabat di jajaran yudikatif. Dengan kata lain, mereka inilah yang really menjalankan pemerintahan. Jadi, kalau disebut demokrasi adalah pemerintahan "oleh" rakyat, sang rakyat ini tidak lagi tergolong pada kategori A, tapi pada kategori B, lebih-lebih bila hanya partai politik yang berhak mencalonkannya untuk dipilih.
Sesudah "berpesta demokrasi", sebagai warga abstrak dari negeri, dia, rakyat A, kembali ke masyarakat sipil selaku "makhluk riil dan konkret" yang didefinisikan tidak berdasarkan hakikatnya atau kesamaannya dengan suatu tipe ideal, tapi menurut partikularitas bawaan dari kedudukan/profesi tertentu, yang disodorkan kepadanya oleh suatu situasi fungsional tertentu. Maka makhluk riil dan konkret ini adalah "manusia situasional". Dia adalah pencari nafkah. Menurut profesi yang ditekuninya, dia bisa disebut apa saja: buruh/pegawai, guru, wartawan, perajin, sopir, petani, nelayan, pengusaha, prajurit, dan lain-lain, yaitu rakyat C.
Sebutan tersebut berlaku menurut ciri-ciri konkret, empiris, dan khas. Namun kekhasan dari pencari nafkah itu tidak termasuk dalam politik dan negara karena manusia yang punya akses ke politik dan negara adalah pemilih, yaitu warga, makhluk abstrak, rakyat A, yang menetapkan eksistensi rakyat B, yaitu elite politik yang, pada gilirannya, bertugas mengurus rakyat C karena peran politik elite adalah (seharusnya) melayani dan menciptakan warga yang puas, warga selaku rakyat C. Dengan kata lain, kalaupun dikatakan demokrasi adalah pemerintahan "untuk" rakyat, sang rakyat ini dari kategori C. Namun tidak jarang dia kemudian disia-siakan, dibiarkan memecahkan sendiri masalah kehidupan yang dihadapinya selaku pencari nafkah, karena pilih kasih elite politik (rakyat B). Elite inilah yang sebenarnya terus "berpesta demokrasi".
Ada "harga finansial" yang perlu dibayar untuk bisa menjadi anggota elite, berupa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya iklan di media massa dan setoran pada kas parpol. Keanggotaan elite ini memungkinkannya menjadi raja kecil, OKB, dan mendirikan dinasti politik demi mempertahankan kenikmatan pesta demokrasi bagi anak-cucunya.
Bagi rakyat kategori A dan B, "harga virtual" yang harus dibayar untuk bisa berdemokrasi adalah keharusan mereka mendelegasikan otoritas dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Maka, demi mengelakkan kekecewaan dalam berdemokrasi, praksis demokrasi harus mampu memuaskan secara seimbang kepentingan ketiga kategori rakyat tadi sesuai dengan wataknya masing-masing.
Sementara itu, setiap warga dewasa perlu menyadari bahwa yang dia delegasikan kepada orang lain adalah otoritas, bukan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan dalam rangka masyarakat sipil. Hal ini berpeluang besar terwujud bila pihak eksekutif melaksanakan pembangunan nasional menurut konsep yang mensinergikan pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.
Lalu monopoli parpol dalam pencalonan orang untuk dipilih perlu dibatalkan. Harus dimungkinkan pencalonan oleh serikat pencari nafkah dan individu independen bagi dirinya sendiri yang selama ini telah membuktikan soliditas pengetahuan (pendidikan) dan pengalaman kerjanya (kemampuan teknis) serta loyalitasnya kepada negeri. Bukankah semua parpol dewasa ini nyaris tidak lagi berdasarkan "ide filosofiko-politis besar", tapi wacana teknis kesejahteraan rakyat? Kemudian, setiap calon, siapa pun yang mencalonkannya, adalah warga yang tidak pernah dihukum karena perkara pidana.
Last but not the least, begitu seorang calon politikus dari parpol dan serikat pencari nafkah terpilih dan ditetapkan menduduki jabatan politis di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, loyalitasnya harus beralih ke negeri, bukan lagi kepada parpol atau ormas induknya.
Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1978-1983
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/15/KL/mbm.20100315.KL132978.id.html
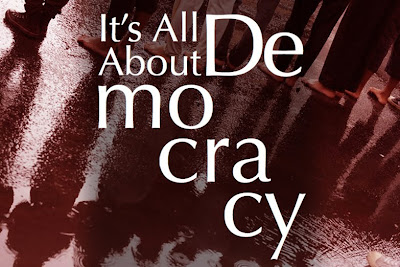


No comments:
Post a Comment