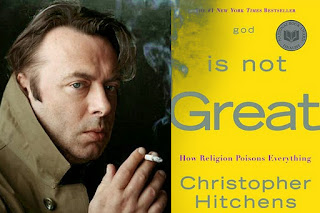Barangkali karena lazimnya, jarang sekali kita memperhatikan bahasa yang kita pergunakan. Bahasa sudah kita anggap sebagai hal yang biasa, seperti makan, minum, dan bernapas. Tetapi sebenarnya, bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan hal paling penting yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah kemampuan berbahasa. Seperti dikatakan oleh Quintilian: “Tuhan, sang Pencipta Alam yang Maha Kuasa serta Arsitek Dunia, telah memberikan kepada manusia suatu sifat yang sangat tepat untuk membedakannya dari pada hewan, yakni daya bicara”. [Mario Pei, 1971].
Mayoritas umat Islam di seluruh dunia sepakat bahwa bahasa al-Qur’an adalah bahasa Arab, dan Nabi Muhammad juga bangsa [orang] Arab. Karena al-Qur’an adalah Kitab Sucinya orang Islam, dan Kitab Suci tersebut berbahasa Arab, maka banyak orang yang menyamaratakan -termasuk para orientalis- bahwa semua yang berbau Arab [Timur Tengah] adalah Islam. Tetapi bila kita cermati lebih dalam lagi, kesimpulan tersebut sebenarnya masih terlalu umum dan terlalu tergesa-gesa. Oleh karenanya amat wajar bila timbul pertanyaan: “Kalau memang benar bahasa al-Qur’an adalah bahasa Arab, dan Nabi Muhammad adalah bangsa Arab, maka Arab yang manakah yang dimaksudkan? Apakah Arab Badui, Arab Palestina, Arab Yaman, Arab Mesir, Arab Himyar, Arab Quraisy, atau Arab Hadramaut?”
Ditinjau dari sejarahnya, paling tidak bisa kita ketahui adanya dua jenis klan besar Arab yang mendiami daerah Hijaz [jazirah Arab]. Yang pertama adalah Arab asli [true Arabs] atau Arab al-‘Ariba dan yang kedua adalah Arab pendatang [arabized Arabs] atau Arab al-Musta’raba. Arab asli adalah keturunan dari Qahtan, sedangkan Arab pendatang merupakan keturunan dari Ismail, yang datang dari Babylonia [Mesopotamia].
Pada masa menjelang lahirnya Muhammad, Mekah sebagai pusat kota yang terpenting pada saat itu -karena terdapat Ka’bah- praktis telah dikuasai oleh orang Arab pendatang yang populer dengan sebutan suku-bangsa Quraisy. Dan seperti kita ketahui, Muhammad adalah salah satu dari keturunan Quraisy yang sejak mudanya mendapat julukan al-Amin. Didukung oleh persekutuan antar kabilah yang kuat dalam perjanjian hilf ul-fudhul, maka bahasa Arab Quraisy secara de facto telah menjadi lingua franca [bahasa utama] di seluruh jazirah Arab pada masa itu.
Berdasarkan data sejarah di atas dan bukti dari berbagai ayat al-Qur’an dapat disimpulkan bahwa bahasa al-Qur’an adalah bahasa kaumnya [bi lisani qaumihi], dalam hal ini kaumnya Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy. Sehingga secara spesifik bisa dikatakan bahwa bahasa al-Qur’an adalah bahasa Arab Quraisy, dan untuk singkatnya disebut dengan bahasa Araby.
Kenapa kita memakai istilah Araby? Apakah kata Araby berbeda dengan Arab? Istilah Araby berasal dari kata Arab yang ditambah dengan huruf “ya nisbah”, yaitu huruf “ya” yang terletak di akhir sebuah kata. Dalam konteks bahasa, “ya nisbah” berfungsi untuk merumpunkan suatu bahasa dengan kelompoknya. Seperti halnya bahasa Indonesia adalah serumpun dengan bahasa Malaysia, yakni termasuk dalam rumpun bahasa Melayu.
Jadi yang kita maksud bahasa al-Qur’an sebagai bahasa Araby adalah karena bahasa Arab Quraisy yang dipakai al-Qur’an tersebut serumpun dengan bahasa Arab seumumnya. Yang penting digarisbawahi di sini adalah, dari dua bahasa yang serumpun sering kali tidak sama persis antara yang satu dengan lainnya. Ada beberapa hal yang sama tetapi banyak pula hal lain yang berbeda.
Bahasa Arab sebagai bahasa asli
Apabila kita perhatikan kata ardl dalam al-Qur’an, kemudian kita bandingkan dengan earth [Inggris], terra [Italia], terre [Perancis], tierra [Spanyol], erde [Jerman], aarde [Belanda], rat [Jawa], yang dalam bahasa Indonesia artinya bumi, maka dari ketujuh bahasa tersebut ada kemiripan dalam bunyi ucapan [lafazh] dan kesinoniman dalam makna yang dikandungnya. Dan bila ada pertanyaan, bahasa manakah yang paling tua umurnya? Untuk menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah.
Tetapi ada seorang dosen linguistik di sebuah universitas terkemuka di Inggris, Prof. Dr. Tahiyya Abdul Aziz yang menulis buku berjudul Arabic Language The Origin of Languages. Dalam buku tersebut, Prof. Tahiyya berani menyimpulkan dengan pasti, bahwa bahasa Arab merupakan sumber dan asal-usul dari semua bahasa yang ada di muka bumi ini.
Sungguh pun bahasa Arab itu dipandang dari sudut literatur adalah bahasa yang termuda di antara kumpulan bahasa-bahasa Samyah [Semite], tetapi bahasa ini lebih banyak mewarisi sifat-sifat asli bahasa induknya, bahasa Samyah, daripada bahasa Ibrani dan lain-lain bahasa yang bersaudara dengan itu [Philip K. Hitti, Dunia Arab, Sejarah Ringkas, hal. 11]. Dan tanah Arablah negeri asal dari cikal-bakal suku-suku bangsa bani Samyah, yaitu bangsa Babylonia, Assyria, Chaldea, Amoryah, Aram, Phunisia, Ibrani, Arab dan Abessinia [hal. 12].
Dalam Kitab Perjanjian Lama [The Old Testament] dikatakan: “Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya.” [Kejadian 11: 1]. Kemudian dalam The Story of Language [Kisah daripada Bahasa], Mario Pei mengutip pernyataan Cowper: “Para sarjana filologi, yang memburu sebuah suku-kata terengah lewat ruang dan waktu, mulai di rumah dan mengejarnya dalam gelap-gulita, ke Gallia, ke Yunani, ke Bahtera Nabi Nuh juga”.
Dari pernyataan tersebut di atas, yang kemudian dihubungkan dengan Surat ash-Shaaffaat ayat 83 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar pendukung dan pelanjut dari Nuh. Lalu disambung dengan Surat al-A’laa ayat 18 dan 19, yang secara tegas menyebutkan bahwa al-Qur’an ini adalah kelanjutan dari shuhuf-shuhuf sebelumnya, yakni shuhuf Ibrahim dan Musa, maka nampaklah jalinan yang tak terputus yang menghubungkan antara al-Qur’an hingga sampai kepada Nabi Nuh. Dan bila sudah sampai Nabi Nuh, maka untuk menghubungkannya hingga Nabi Adam ibaratnya tinggal selangkah lagi, yakni terhubung melalui Nabi Idris.

Yang dimaksud dengan shuhuf para Nabi adalah ajaran beserta bahasanya. Sehingga yang disebut sebagai Arabic language oleh Prof. Tahiyya sebagai asal-usul semua bahasa di dunia ini, lebih tepat kiranya bila dikatakan sebagai bahasa wahyu yaitu bahasa para Nabi, sejak Adam sampai Muhammad. Jadi dalam kaitan hubungannya dengan bangsa Arab, bukanlah wahyu al-Qur’an yang mengikuti Arab, tetapi bahasa dan budaya Arablah yang mengikuti bahasa dan budaya para Nabi [al-Qur’an, Injil, Taurat, Zabur, Shuhuf Ula, al-Asma dll.].
Bila sejarah timbulnya bahasa dirunut sejak Nabi Adam a.s., sebenarnya kemampuan manusia dalam berbahasa tidak bisa lepas dari pengajaran yang diberikan oleh Allah. Dan karena Adam itu satu, Allah juga satu, maka bahasa pun pada awal mula kelahirannya semestinya hanya satu juga.
Jadi bila dikatakan bahwa bahasa itu adalah ciptaan manusia, kemungkinan besar yang diciptakan oleh manusia hanyalah berupa bentuk tulisannya saja. Sedangkan bahasa dalam bentuk aslinya yang pertama adalah berupa suara atau rangkaian bunyi [ujaran] yang mengandung makna tertentu. Dan bentuk bahasa ucap atau percakapan ini pastilah bukan ciptaan manusia, tetapi pemberian dari Allah, Tuhan Pencipta alam semesta.
Bentuk bahasa al-Qur’an
Bahasa ucap atau bahasa lisan merupakan landasan bagi semua bahasa. Dan bahasa wahyu yang didokumentasikan dalam al-Qur’an disebut sebagai qaulan atau lisaanan yang artinya ucapan atau perkataan lisan. Hal ini perlu kita tandaskan karena perbedaan bentuk bahasa akan berpengaruh pada makna yang dikandungnya.
Sebagai perbandingan antara bentuk bahasa ucap dan bahasa tulis, bisa kita kemukakan disini, antara lain:
1. Bahasa tulis sangat terikat oleh tata bahasa, sedangkan bahasa ucap lebih longgar dalam hal gramatikanya.
2. Dalam bahasa ucap, intonasi atau tinggi rendah tekanan [nada] suara sangat mempengaruhi makna yang dikandungnya, sementara dalam bahasa tulis tidak ada persoalan ini.
3. Pihak-pihak yang berbicara biasanya saling bertemu secara langsung dengan tatap muka dialogis dan interaktif, sedangkan dalam bahasa tulis tidak demikian.
4. Yang paling tahu maksud dari suatu ucapan adalah si pengucap itu sendiri. Bila tidak mengerti bisa langsung bertanya. Sedang dalam bahasa tulis, biasanya banyak sekali pemahaman, tafsiran dan interpretasi yang bahkan kadang-kadang bertolak belakang dengan maksud si penulis.
Dengan memahami bahwa bahasa al-Qur’an sebenarnya adalah bahasa ucap atau bahasa lisan yang ditulis [diabadikan] dalam mushkhaf, maka kita bisa lebih berhati-hati terutama dalam upaya untuk melagukan atau menyanyikan al-Qur’an. Jangan sampai sebuah kisah yang ‘heroik’ di dalam al-Qur’an [misalnya Surat al-Kafirun] menjadi terdengar ‘lucu’ karena melagukannya keliru dengan nyanyian meratap. Atau sebaliknya, yang seharusnya meratap menadahkan harapan dalam suasana syahdu, tapi malah dinyanyikan dengan semangat berapi-api.
Disamping hal itu, walaupun mempelajari tata bahasa itu penting, tetapi al-Qur’an sebagai bentuk bahasa ucap atau lisan mempunyai teori gramatika [tata bahasa] tersendiri. Tidak cukup hanya dengan sekedar belajar Nahu Sharaf dari Tata Bahasa Arab biasa. Singkatnya, untuk belajar bahasa al-Qur’an memang harus mempelajari Tata Bahasa al-Qur’an.
Dalam al-Qur’an Surat al-Haaqqah: 38 – 43 diterangkan bahwa bahasa al-Qur’an adalah bahasa percakapan dari Tuhan Pencipta alam semesta kepada Utusan-Nya yang dari segi bentuk maupun kandungannya mempunyai nilai yang sangat mulia [qaulu rasuulin kariimin].
Dibandingkan dengan bentuk bahasa sastrawan atau penyair [syaa’irin] yang terlalu berorientasi pada keindahan lahiriahnya saja, baik keindahan bentuk bait-bait sajaknya atau merdunya nada dan irama lagunya, al-Qur’an ternyata bukan termasuk bahasa semodel itu.
Bentuk bahasa al-Qur’an juga bukan bahasa manterawan [kaahinin] atau peramal, dukun, dan lain-lain sebutan bagi orang ‘pintar’ yang ngerti sakdurunge winarah [tahu segala peristiwa sebelum terjadi]. Karena bentuk bahasa model ini sering kali sulit dinalar dan tidak komunikatif, maka biasanya memerlukan juru tafsir khusus. Misalnya, karya-karya ramalan Jangka Jayabaya, Ronggowarsito atau Nostradamus. Juga kalimat-kalimat mantera dan tulisan-tulisan rajah yang sering dipakai untuk jimat.
Dari semua bentuk bahasa tersebut di atas, baik yang syaa’irin maupun kaahinin yang tahu hanya para tokohnya dan juru tafsirnya saja. Semakin sulit dipahami akan semakin hebat, dan tentu saja semakin mahal harganya.
Paradoks bahasa
Dalam al-Itqan, as-Suyuthi mengatakan: “Barang siapa menyatakan telah memahami rahasia-rahasia yang tersimpan dalam al-Qur’an, tetapi tidak menguasai makna lahiriahnya [tekstual], maka ibaratnya sama dengan orang yang mengatakan bahwa dia telah sampai [masuk] di tengah sebuah rumah, tetapi tidak melewati pintunya”. Dari pendapat as-Suyuthi ini, terlihat dengan jelas bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami makna suatu bahasa tanpa mempelajari bahasa yang bersangkutan.
Akan tetapi pengalaman kita dalam belajar bahasa membuktikan bahwa, bahasa sebagai alat untuk menyampaikan makna sama sekali tidak menentukan makna yang dikandungnya. Misalnya kata “bisa” mempunyai makna “dapat” atau “racun”. Dalam kasus ini sebuah lambang bahasa mempunyai kandungan makna lebih dari satu. Kadang-kadang dalam kasus yang lain, satu makna yang sama tetapi diungkapkan dengan lambang bahasa yang berbeda-beda, contohnya kata “ibarat”, “umpama”, “misal”, “bagaikan”, “seperti”, “penaka”, dan lain sebagainya, walau diungkapkan dengan istilah yang berbeda-beda tetapi maksudnya tetap sama.

Demikian inilah paradoks bahasa, di satu segi kita harus melalui bahasa untuk mempelajari makna yang dikandungnya, di segi yang lain kita tidak boleh terjebak pada bahasa sebagai alat penyampai makna yang sama sekali tidak menentukan makna itu sendiri. Bahasa sebagai alat ibaratnya seperti sebuah keranjang [wadah], apakah isi keranjang itu batu, buah-buahan atau pakaian, tidak ditentukan oleh keranjang itu sendiri. Paling-paling orang hanya bisa menduga berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kebiasaannya, kalau keranjangnya model seperti itu maka biasanya untuk tempat buah, dan kalau yang bentuknya begini biasanya untuk tempat pakaian dan seterusnya.
Bila bahasa hanya sekedar alat atau sarana untuk menyampaikan makna, yang jadi pertanyaan adalah apakah atau siapakah sebenarnya yang paling menentukan makna dari suatu bahasa?